Ha Giang, sebuah provinsi paling Utara Vietnam yang berbatasan dengan China, inilah tempat yang jadi tujuan utama saya dalam perjalanan kali ini. Setelah beberapa drama dengan publik bus lokal dari Hanoi yang lebih dari penuh dan berhenti tiap beberapa menit, setelah 6 jam perjaanan sekitar pukul 11 malam kemarin kami sampai (jika sempat, saya akan buat cerita terpisah tentang ini). Udara malam yang dingin tanpa angin menyalami kami dengan lembut. Akhirnya!

Keesokan harinya saat membuka mata, saya disambut dengan bekas hujan tadi subuh. Kabut di leher-leher gunung masih menggantung malas. Ritme kota ini mau tak mau membuatmu melambat. Berlama-lama menghabiskan waktu di dalam selimut atau sekedar duduk manis memandang sungai, ya saya selalu mencoba mencari hotel dengan pemandangan, jika sesuai kocek nan terbatas ini.
Setelah menunaikan segala tugas, heeh saya bawa-bawa kerjaan lagi jalan. (Hal yang ga terlihat tapi suer ga pake boong, saya masih butuh mencari sepiring nasi dan sebakul berlian *eh) Setelah siang, bunyi genderang perut nan lapar akhirnya menjadi alarm yang menyeret saya untuk beranjak dari hotel.
“Makan apa?” pertanyaan yang selalu muncul ketika lapar. Hal susah-susah gampang saat berjalan di negara lain dan kota kecil. Dengan bantuan google map, saya menyeret kaki berjalan. Kota ini sepi, dengan jalan-jalan lebar dan gunung-gunung tinggi yang mengelilingi. Setelah berjalan sekitar 15 menit saya dan teman menemukan sebuah warung makanan ya buka, ya beberapa kedai lain sudah tutup di saat itu. Untuk informasi seberapa sepi dan selownya kota ini, saya berjalan sekitar pukul 13.30 siang.
Warung ini masih buka dan masih ada beberapa orang lokal yang sedang makan di dalamnya. Ragu-ragu kami masuk atas tuntutan perut. Perempuan yang sedang duduk mengoreng memandang saya, bercakap dalam bahasa Vietnam yang jelas tak saya mengerti. Fakta tak terbantah, bermuka Asia membuatmu sering kali diidentikkan dengan penduduk lokal.
Maka dimulailah cara komunikasi paling purba, body language. “That..” saya menunjuk. Lalu dijawab kembali dalam bahasa Vietnam. “How much?” saya belajar dari pengalaman, untuk pertama-tama memastikan harga dari apa yang kamu makan sebelum memesan.
Dia menjawab dalam bahasa Vietnam, saya mengulurkan handphone dalam mode kalkulator. “35” dia mengetik di sana.
Saya tersenyum, “one” sembari tangan memperlihatkan telunjuk, lalu duduk.

Tak berapa lama, makanan kami datang dalam 1 nampan besar. Mereka memandang kami dengan rasa ingin tau, melihat dan memastikan. Kami bertukar senyum berkali-kali. Lalu salah satu pegawai di sana mendatangi, menunjukkan cara tepat untuk memakan makanan yang terakhir saya tau namanya bun cha. Setiap melewati kami mereka melirik dengan perhatian. Memberikan kami extra mie beras dan memastikan kami mendapatkan teh terbaik. Kami jadi tamu terakhir sebelum mereka tutup.
Setelah pengalaman buruk yang terjadi di Hoi An, tiba-tiba saya merasa haru. Akh.. saya serasa anak hilang yang pulang di sini. Meski saya tak paham bahasa mereka, saya bisa merasakan perhatiannya yang teramat tulus. Ada 3 perempuan di kedai itu, ketiganya tak berhenti tersenyum setiap lewat. Menawarkan saos tambahan, teh tambahan bahkan bawang goreng tambahan. Hangat.
Ini satu dari banyak hal yang selalu dirindukan saat berjalan. Interaksi dengan penduduk sekitar. Betapa luar biasa manusia dengan segala perbedaan tetap bisa saling memperhatikan dan membantu.
Bahasa tubuhmu adalah bahasa universal yang mampu dipahami di mana saja.
HaGiang, 2018-3-15
Ivy
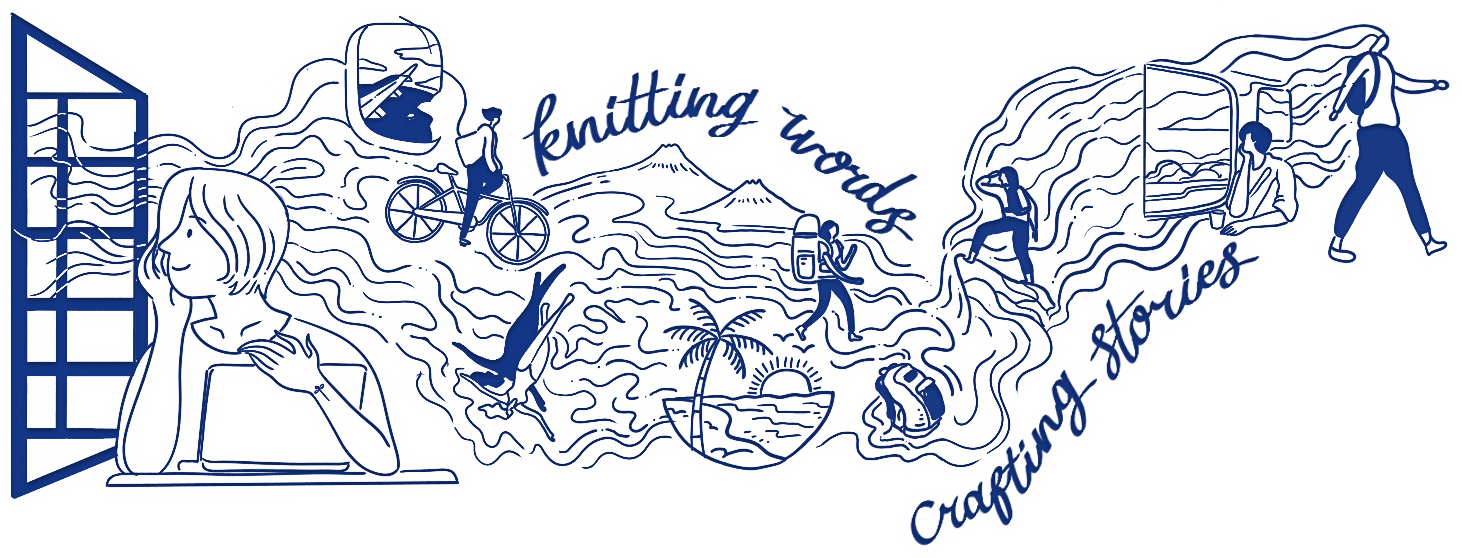




Leave a Reply